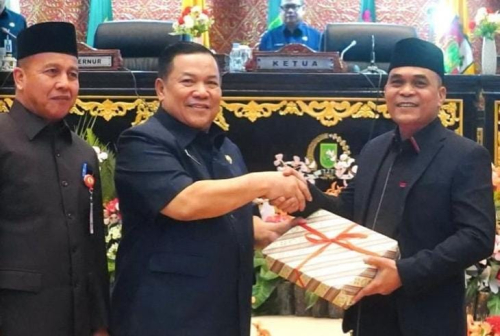Oleh: [Guswanda Putra, S.Pi/Pemerhati Kebijakan Publik]
Pekanbaru, Riau, saat ini berada di persimpangan antara harapan besar dan kekhawatiran yang mendalam. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau, sebagai salah satu kepala daerah dengan sumber daya alam terbesar, seharusnya menjadi momentum penegasan hukum tanpa cela. Namun, alih-alih menampilkan penindakan yang sempurna, perkembangan di lapangan menunjukkan situasi yang kontradiktif: KPK dikabarkan menghadapi kesulitan fundamental dalam mematangkan bukti dan terus menerus memburu saksi baru setelah penetapan tersangka. Kondisi ini bukan hanya menunda keadilan, tetapi juga memunculkan paradoks prosedural yang sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menjadi bumerang bagi lembaga anti-rasuah itu sendiri.
Kemerosotan Kualitas Bukti: Melawan Semangat KUHAP
Inti dari OTT, sebagai instrumen pamungkas KPK, adalah penindakan yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup, sesuai amanat Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menuntut minimal dua alat bukti yang sah. OTT seharusnya menjadi kulminasi dari proses intelijen dan pengumpulan bukti yang solid, bukan permulaan dari pencarian bukti.
Ketika KPK dipaksa untuk melakukan perburuan saksi dan alat bukti secara masif setelah penahanan pejabat publik sebuah langkah yang lazim dilakukan dalam penyidikan kasus yang tidak berawal dari OTT hal ini secara tidak langsung mengakui cacat fundamental pada bukti awal yang digunakan untuk penangkapan. Pertanyaan kritisnya adalah: Jika dua alat bukti yang cukup belum solid, atas dasar apa penahanan seorang pemimpin daerah dilakukan? Penahanan tanpa bukti yang matang adalah pelanggaran terhadap semangat KUHAP, karena proses penahanan dijadikan dasar untuk mencari bukti, bukan bukti yang solid menjadi dasar untuk penahanan. Inilah titik krusial yang mengikis legitimasi proses hukum.
Pelanggaran Batas Penyelidikan dan Penyidikan
Secara hukum, OTT berada di antara tahapan penyelidikan (inquiry) dan penyidikan (formal investigation). Loncatnya proses langsung ke penahanan berarti KPK mengklaim sudah memiliki bukti prima facie yang tak terbantahkan. Mencari saksi secara gencar setelah penahanan mengimplikasikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara terbalik—menetapkan subjek dulu, baru mencari alat bukti yang mendukungnya.
Praktik ini mengaburkan esensi OTT dan menggantinya dengan praktik yang menyerupai "Trial by Error" atau fishing expedition. Pelanggaran batas ini bukan hanya sekadar teknis, tetapi menyentuh legalitas penahanan dan hak asasi tersangka. Jika pengadilan menemukan bukti awal tidak cukup, seluruh proses OTT yang mahal dan berisiko tinggi dapat digugat, yang akan menghancurkan kredibilitas KPK.
Risiko Kriminalisasi dan Preseden Buruk
Pengejaran bukti yang terkesan dipaksakan pasca-OTT membawa risiko serius, yakni kriminalisasi atau rekayasa kasus. Penyidik berada dalam tekanan besar untuk mempertahankan narasi OTT yang sudah terlanjur dipublikasikan. Tekanan ini dapat mendorong penyidik untuk mencari saksi yang "mencocokkan" kesaksiannya dengan konstruksi kasus yang sudah dibuat, yang dapat mengindikasikan adanya unsur mala fide (itikad buruk) dalam penanganan kasus.
Risiko ini ditegaskan oleh akademisi. Dr. Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, berpendapat:
“Logika sebuah OTT seharusnya sudah didukung oleh bukti yang matang. Jika setelah penahanan KPK masih harus mati-matian mencari saksi baru, ini mengindikasikan bahwa bukti awal yang dijadikan dasar penetapan tersangka tidaklah memadai. Praktik seperti ini dapat mencederai integritas proses hukum, menjadikan proses pemberantasan korupsi terkesan seperti upaya memaksakan konstruksi kasus, alih-alih penegakan hukum berdasarkan bukti yang kuat dan sah.”
Sikap KPK ini berpotensi menciptakan preseden buruk di masa depan, di mana asas praduga tak bersalah dikorbankan demi sensasi penindakan cepat. Masyarakat akan mulai curiga: apakah penindakan ini didorong oleh bukti kuat, ataukah didorong oleh desakan popularitas?
Dampak Ganda: Stabilitas Politik dan Ekonomi Riau
Implikasi dari proses hukum yang berlarut-larut dan diragukan validitas buktinya ini melampaui ruang sidang, langsung menyentuh stabilitas regional Riau:
1.Kemandekan Birokrasi: Ketidakpastian hukum di pucuk pimpinan provinsi Riau menciptakan kekosongan kepemimpinan yang berpotensi melumpuhkan proses pengambilan kebijakan strategis, terutama terkait pengadaan barang dan jasa publik serta persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ribuan program pelayanan publik dapat tertunda karena ketidakberanian pejabat di bawahnya mengambil keputusan.
2.Iklim Investasi: Riau adalah lumbung energi dan perkebunan Indonesia. Investor sangat membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas politik. Proses hukum yang terlihat "goyah" ini mengirimkan sinyal negatif, meningkatkan risiko politik, dan menghambat aliran investasi vital yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi regional.
3.Efek Psikologis Pegawai: Aparatur Sipil Negara (ASN) di Riau akan cenderung bermain aman (wait and see), yang secara kolektif memperlambat laju pembangunan dan menghambat inovasi.
Rekomendasi Institusional: Pemulihan Integritas Prosedur
Untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan integritas proses hukum, diperlukan tindakan institusional yang tegas dan multi-pihak:
1. Audit Prosedural oleh Dewan Pengawas (Dewas): Dewas KPK harus segera mengambil peran aktif untuk mengaudit prosedur OTT dan penetapan tersangka, memastikan kepatuhan terhadap standar minimum dua alat bukti yang cukup sebelum penahanan. Kegagalan Dewas meninjau hal ini sama saja dengan melanggengkan praktik prosedural yang cacat.
2. Keterlibatan Ombudsman RI: Ombudsman Republik Indonesia perlu turun tangan mengawasi potensi maladministrasi dalam proses penyidikan, terutama terkait dugaan adanya fishing expedition yang mengancam hak-hak hukum terperiksa.
3. Transparansi Bukti Awal: KPK harus memberikan klarifikasi terbuka dan terperinci (sesuai batasan hukum) mengenai sifat dan bentuk bukti awal yang menjadi dasar penangkapan, bukan hanya bergantung pada narasi yang ambigu.
4. Fungsi Pengawasan DPR RI: Komisi III DPR RI perlu menggunakan fungsi pengawasannya secara efektif untuk meminta pertanggungjawaban KPK mengenai efisiensi dan kehati-hatian dalam penindakan. Sejarah akan mencatat apakah parlemen memilih membela prosedur yang benar atau membiarkan institusi penegak hukum mengorbankan legalitas demi sensasi.
Pemberantasan korupsi adalah keharusan mutlak bagi masa depan bangsa, tetapi ia harus dilakukan dengan cara yang bermartabat dan taat hukum. Integritas prosedur adalah benteng terakhir KPK. Jika benteng itu runtuh karena sensasi OTT yang tidak didukung bukti matang, maka yang hancur bukan hanya kasus ini, tetapi juga fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga anti-rasuah di Indonesia.***
#KPK RI #OTT KPK Abdul Wahid